Moderasi Indonesia di Mata Muhammad al-Ghazali: Sebuah Refleksi Kritis
"Menggali kritik tajam Muhammad al-Ghazali (kontemporer) terhadap konsep moderasi di Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar moderat, ataukah ada esensi yang terabaikan?"
Indonesia dan Moderasi Islam
Indonesia kerap merayakan dirinya sebagai model moderasi Islam global, mengusung narasi "Islam Nusantara" dan program "Moderasi Beragama" yang digalakkan pemerintah. Namun, bagaimana konsep moderasi ala Indonesia ini akan terlihat jika dibedah dengan lensa pemikiran Muhammad al-Ghazali (1917–1996), seorang ulama dan pemikir Mesir kontemporer yang gigih menyerukan kebangkitan umat dan penegakan keadilan Islam?
Al-Ghazali, dalam bukunya "Mi'ah Su'al 'an al-Islam", khususnya pada sub-judul "Ma Ma'na Anna Allah Ja'alal Muslimin Ummatan Wasatan" (Apa Makna Allah Menjadikan Muslim Umat yang Moderat), menegaskan bahwa moderasi adalah jalan lurus yang menolak dua ekstrem: berlebihan (ghuluw) yang cenderung pada fanatisme dan kekurangan (tafrit) yang berujung pada kelalaian. Baginya, ekstremisme lahir dari kesalahan berpikir dan hati yang bengkok, menjauhkan dari kebenaran Islam yang murni. Dengan kacamata inilah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kritis terhadap praktik moderasi yang sering diklaim di Indonesia.
Ketika Toleransi Mengalahkan Penegakan Kebenaran?
Konsep moderasi di Indonesia sangat menekankan toleransi antarumat beragama, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal. Ini adalah fondasi penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman. Namun, dari perspektif Al-Ghazali, muncul pertanyaan: Apakah penekanan pada toleransi ini terkadang mengaburkan kewajiban untuk menegakkan kebenaran Islam dan memerangi penyimpangan, sebagaimana yang diserukan oleh Islam untuk "amar ma'ruf nahi munkar"?
Dalam pembahasannya tentang makna umat pertengahan, al-Ghazali mengamati bagaimana pepatah lama tentang keutamaan sebagai jalan tengah antara dua keburukan seringkali hanya menjadi teori belaka. Ia menegaskan, pada kenyataannya, kebenaran telah tersesat di antara dua ekstrem: berlebihan yang merusak, dan kelalaian yang tak acuh. Akibatnya, umat manusia menderita, terjebak di antara ekstremisme yang membakar dan kelalaian yang membekukan. Ghazali menyoroti bagaimana sebagian umat berlebihan dalam ibadah hingga terjebak bid'ah, sementara yang lain terlalu lalai hingga berujung pada sikap tidak bersyukur dan durhaka.
Jika moderasi di Indonesia lebih fokus pada tidak menyinggung pihak lain, menghindari konflik permukaan atau menjaga status quo demi kerukunan, apakah ia berisiko mengabaikan substansi penegakan keadilan dan pelurusan aqidah yang dianggap Al-Ghazali sebagai esensi moderasi? Apakah dalam upaya menjadi toleran, kita menjadi terlalu permisif terhadap praktik-praktik yang secara fundamental menyimpang dari Islam, atau terhadap korupsi dan ketidakadilan yang merajalela hanya demi mempertahankan citra "moderat"?
Kekeringan Hati di Balik Lisan yang Fasih
Al-Ghazali secara pedih mengkritik kondisi di bidang ilmu agama. Ia menyaksikan banyak orang sangat menguasai teks-teks agama, memiliki pengetahuan luas dan banyak hafalan. Namun, ironisnya, hati mereka diliputi kekeringan ekstrem, terputus dari esensi spiritual dan keadilan. Beliau mengamati bagaimana ulama yang demikian bisa menjadi kaku dalam pengambilan keputusan atau kurang memiliki empati dalam memberikan fatwa, bahkan ketika berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan kebijaksanaan dan belas kasih. Ini adalah gambaran bagaimana ilmu tanpa hikmah dan hati nurani bisa menjadi petaka.
Al-Ghazali juga menyayangkan pemisahan antara fikih (hukum Islam) dan tasawuf (mistisisme Islam). Menurutnya, perpecahan ini terkadang membuat para sufi ekstrem hingga 'gila' karena hanyut dalam spiritualitas tanpa pijakan, dan di sisi lain, menjadikan para ahli hukum kaku serta tidak peka. Dalam konteks Indonesia, di mana perdebatan fikih seringkali mengeras tanpa sentuhan tasawuf, dan praktik spiritualitas kadang terpisah dari syariat, kritik Al-Ghazali ini menggema kuat. Apakah moderasi kita telah berhasil menyatukan dimensi akal dan hati, ataukah kita masih bergulat dengan perpecahan internal yang ia khawatirkan?
Moderasi Sosial dan Ekonomi: Lebih dari Sekadar Kosmetik
Moderasi, menurut Al-Ghazali, adalah prinsip yang nyata dalam ajaran sosial dan ekonomi Islam. Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, ia menolak keras praktik pembelengguan perempuan atau pandangan laki-laki yang merendahkan mereka seperti pandangan sipir penjara terhadap para tahanan, atau pandangan pemburu terhadap mangsanya.
Bagi Al-Ghazali, rumah adalah inkubator penting tempat perempuan bertanggung jawab membesarkan generasi baru, namun ia bukanlah penjara. Ia menekankan peran perempuan yang aktif dalam masyarakat: belajar, mengajar, hingga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan bahkan membela diri ketika terjadi peperangan. Apakah moderasi di Indonesia telah sepenuhnya membebaskan perempuan dari belenggu adat yang keliru dan pandangan yang merendahkan?
Secara ekonomi, Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa Islam mengakui hak milik pribadi, namun membatasinya demi mencegah korupsi, eksploitasi, dan tindakan terlarang, sekaligus melindungi kaum lemah. Dalam pandangannya, sistem ekonomi Islam menjamin terciptanya produksi yang melimpah tanpa mengorbankan keadilan sosial, sehingga mampu mencegah disintegrasi masyarakat. Al-Ghazali sangat kritis terhadap dua kutub ideologi ekstrem: kapitalisme yang tidak adil dan komunisme ateis. Ia meyakini bahwa Islam hadir sebagai jalan tengah yang menyelamatkan manusia dari ketimpangan kedua sistem tersebut.
Sebelum Islam, menurutnya, kaum Yahudi terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap uang—termasuk praktik riba—sementara umat Kristen cenderung berlebihan dalam asketisme dan meninggalkan kehidupan duniawi. Islam menolak kedua ekstrem ini dengan menempatkan uang sebagai sarana untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Ghazali menyerukan agar umat Islam kembali kepada sistem ekonomi yang moderat dan adil, berlandaskan syariat. Dalam pandangannya, uang adalah penopang kehidupan, bekerja adalah bentuk ibadah, dan semuanya harus dilakukan dalam koridor kehalalan serta demi perlindungan terhadap kaum yang lemah.
Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia—dari bank, asuransi, hingga produk halal—Muhammad al-Ghazali mungkin akan bertanya dengan tajam: Apakah label "syariah" yang melekat pada sistem ini sungguh mencerminkan keadilan ekonomi substantif yang menjadi cita-citanya? Ataukah istilah tersebut hanyalah kosmetik religius yang membungkus praktik-praktik kapitalisme konvensional, dengan kesenjangan sosial yang tetap lebar dan akumulasi kekayaan yang masih terpusat pada segelintir elite?
Bagi Al-Ghazali, sekadar menghindari riba tidaklah cukup. Ia akan menuntut agar kekayaan tidak hanya halal secara teknis, tetapi juga berfungsi sosial—disalurkan untuk menopang kaum yatim, miskin, dan kaum dhu’afa. Ia akan mempertanyakan apakah sistem ini benar-benar memihak kepada yang lemah atau justru melanggengkan dominasi ekonomi oleh kelompok kuat dengan balutan religiusitas simbolik.
Dalam kerangka pemikirannya, keadilan tidak bisa hanya berhenti pada aspek formalistik atau legalistik, melainkan harus nyata dalam distribusi, perlindungan terhadap yang rentan, dan penghapusan ketimpangan struktural. Maka, kita pun patut bertanya: Sudahkah ekonomi syariah di Indonesia menjelma menjadi sistem yang moderat dan adil seperti yang digariskan Al-Ghazali, atau masih terjebak dalam penampilan formal tanpa ruh keadilan sosial yang sejati?
Tantangan Kesadaran Umat: Antara Nasionalisme dan Manhaj Kenabian
Muhammad al-Ghazali adalah seorang nasionalis Mesir, tetapi nasionalismenya selalu terbingkai dalam identitas keislaman dan kebangkitan umat. Baginya, moderasi eksternal adalah tentang kembalinya umat Islam pada manhaj (metodologi) Nabi dan Sahabat untuk menjadi ummatan wasatan yang aktif menegakkan kebenaran dan menjadi saksi bagi umat manusia.
Konsep moderasi di Indonesia sangat lekat dengan Pancasila dan NKRI sebagai payung pemersatu. Ini adalah kekuatan besar. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Al-Ghazali, pertanyaan kritisnya adalah: Apakah penekanan pada identitas nasional ini terkadang mengaburkan urgensi untuk mengembalikan umat pada manhaj kenabian secara murni dan proaktif dalam menghadapi tantangan global? Apakah ada risiko bahwa "moderasi beragama" justru menjadi sekadar alat stabilitas politik, yang kurang mendorong transformasi moral dan spiritual umat yang mendalam, sebagaimana yang selalu ditekankan Al-Ghazali?
Al-Ghazali akan menantang kita: Apakah kita terlalu sibuk mendamaikan perbedaan di permukaan, sementara penyakit hati yang kering, kesenjangan fikih-tasawuf, atau pemahaman agama yang dangkal terus menggerogoti dari dalam? Tanpa pondasi internal yang kuat dan manhaj yang benar, apakah moderasi eksternal yang kita banggakan akan berkelanjutan?
Menarik Pelajaran dari Al-Ghazali: Menuju Moderasi yang Autentik
Muhammad al-Ghazali menawarkan lensa yang berharga untuk mengkritisi konsep moderasi di Indonesia. Beliau mengingatkan kita bahwa moderasi sejati tidak hanya tentang toleransi pasif atau stabilitas sosial, tetapi tentang keadilan yang aktif, penegakan kebenaran, dan kebangkitan umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang murni.
Al-Ghazali menekankan bahwa Islam menolak penyembahan yang disertai kesombongan, menganjurkan pertobatan, dan menyerukan reformasi yang rendah hati dan lembut. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata: "Ahli Fikih sejati adalah dia yang tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah, juga tidak membuat mereka merasa aman dari tipu daya-Nya!"
Mungkin saatnya kita tidak hanya merayakan moderasi sebagai identitas, tetapi juga mengevaluasi secara jujur, apakah moderasi yang kita praktikkan sudah cukup dalam, substantif, dan transformatif, sebagaimana yang diimpikan oleh Muhammad al-Ghazali untuk umat Islam kontemporer.
Pesan ini adalah pengingat bahwa moderasi bukan sekadar label, melainkan sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, menuntut implementasi nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Al-Ghazali berharap, umat Islam mempelajari kebenaran ini dari Nabi mereka, memahaminya, dan menerapkannya. Sebab, Allah akan bertanya kepada mereka tentang petunjuk yang telah mereka terima: apakah petunjuk itu dimanfaatkan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, atau hanya sebagai hiasan pemanis bibir semata?
Referensi Utama:
Al-Ghazali, Muhammad. Mi'ah Su'al 'an al-Islam (Seratus Pertanyaan tentang Islam). Kairo: Dar Nahdhah Misr, [2014]. Khususnya bab: "Ma Ma'na Anna Allah Ja'alal Muslimin Ummatan Wasatan" (Apa Makna Allah Menjadikan Muslim Umat yang Moderat). hlm. 94–97.

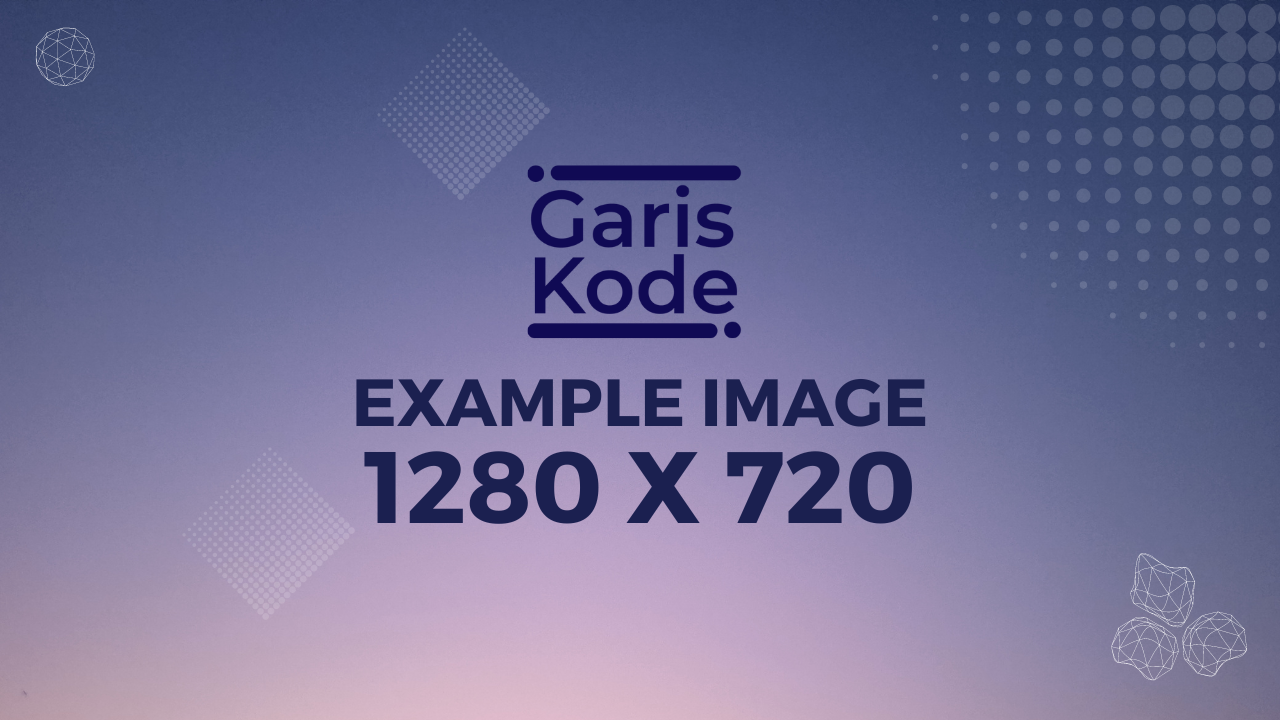


8rnn7a
* * * Snag Your Free Gift: http://mms-gms.ch/index.php?x7n3bn * * * hs=d55c1d56caa0b9700fe225ab74865eaf* ххх* Guest
30 Jul 2025